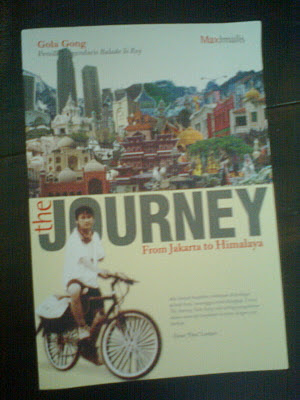Tadi pagi pas disuruh Bapak ambil uang di Kospin di kota Klaten, aku kena tilang polisi loh. Ceritanya kan aku nggak tahu tuh tepatnya mana Kospin di Kota Klaten itu, jadi aku nyari-nyari… tengok kanan tengok kiri mana Kospinnya. Pas ketemu, eh ternyata di kanan jalan. Tepatnya harus belok kanan dan nyebrang jalan kecil kanan jalan raya. Pas aku belok kanan dan hendak parkir di Kospin, tiba-tiba ada polisi dengan motor gedhenya nongol gitu aja di depanku. Terkejut deh aku. Ini polisi kaya hantu aja ngagetin, mau apa dia. Aku mau lewat, eh dicegah. Waaahh mau nangkep aku nih kayanya, pikirku. Aku diem aja donk, nggak mau banget berurusan sama polisi soalnya. Tiba-tiba polisinya nyeletuk, “bisa tunjukkan SIM-nya?!”. Trus aku jawab, “saya mau ke Kospin situ Pak, jadi saya belok kanan soalnya Kospinnya di kanan jalan, apa saya salah?”. “Bisa tunjukkan SIM-nya?!” sekali lagi dengan lebih keras dan ganas. Weeee lha! Menyebalkan sekali polisi satu ini. Nasib nasib… bisa apa aku kalau udah gini, mana cewek lagi aku nggak bisa berkelahi. Yaudah apa mau dikata, aku keluarkan SIM-nya. Sambil diambil kasar SIM-ku direbutnya dari tanganku. “ikut saya di pos depan Matahari”. Hhhggh… seenaknya aja. Udah nggak mau jawab pertanyaan, nyuruh-nyuruh juga. Rasanya pengen ngejatuhin itu polisi dari kendaraannya, sayang sekali motorku kalah gedhe, dan aku nggak bisa ngebut juga.
Sesampai di pos polisi, eh ada orang juga yang kena tilang, bernasib sama sepertiku. Apa maunya polisi sini, pikirku. Nilang orang-orang seenak udelnya. Trus aku disuruh nunggu, katanya antre, ada orang yang kena tilang juga. Lah, kaya mau bayar ke kasir aja pake antre segala. Emang posnya udah mirip kasir gitu deh, kecil banget. Tapi nggak ada kalkulator elektriknya. Adanya Cuma laci dan kertas macam bon atau kwitansi. Hahah! Pemandangan yang bikin ngakak.
Setelah orang yang barusan ditilang selesai urusannya aku disuruh masuk. Tapi aku nggak menggubris si polisi yang menyuruhku masuk, aku malah nanyain orang yang barusan ditilang, “Eh masnya disuruh bayar berapa?” tanyaku. “Nggak bayar, aku minta ke pengadilan aja” jawabnya. “Oh.. ya deh, good luck ya mas” haha… polisinya udah jengkel kayanya liat mukaku. Yealah pak polisi yang terhormat, memangnya aku cewek nggak bisa nggak sopan juga? Memangnya Cuma anda yang bisa nggak sopan? Batinku.
Di dalem pos polisi yang super sempit itu aku disuruh mengeluarkan STNK. Daripada kena umpat mending langsung kukeluarkan STNK-nya. Trus si polisi menjelaskan, “harusnya mbaknya nggak belok kanan, tapi ambil jalur kanan lewat jalan kecil kanan sebelah jalan raya setelah lampu merah sebelum tempat tujuan mbaknya. Itu peraturannya. Paham?!” aku Cuma ngangguk aja. Males banget buat mengeluarkan suaraku yang berharga ini untuk didenger si polisi menyebalkan itu. Ngomong-ngomong, darimana aku harus paham, memangnya peraturan di jalan raya ini macem UUD ‘45 yang harus dihapal dan dipahami tiap-tiap warga Indonesia. Dan lagi peraturan yang barusan diomongin si polisi dan memintaku untuk memahaminya itu adalah peraturan yang aneh pula. Masak mau belok kanan aja dilarang. Setauku belokan dibuat ya fungsinya buat jalan kalau mau belok. Mana kutau juga kalau Kospinnya letaknya disitu, aku juga lagi nyari-nyari tauk! Dikira mukaku mirip peta apa ya sehingga aku harus selalu tau persis setiap tempat tujuanku jadi aku bisa ancang-ancang? Ugh! Menyebalkan. Trus aku sedikit protes juga, “Pak, tadi kok yang ditangkep Cuma saya, kan ada banyak orang juga yang belok situ… nggak adil deh”. Si polisi jawab, “lha kan saya liatnya kamu, nggak liat yang laen, jadi nggak perlu protes!”. Eh! Polisinya bisa juga bikin aku Ge Er! Hwakakaka…
Setelah itu ditanya mau bayar atau mau ke pengadilan, karena tadi ada mas-mas yang milih ke pengadilan aku langsung minta sidang di pengadilan aja. Itung-itung buat tau pengadilan itu kaya apa… hahaha seumur-umur belum pernah aku liat dalem pengadilan secara langsung, ya buat jalan-jalan gitu deh… (jalan-jalan kok ke pengadilan yah, kaya ga ada tempat laen aja, mana pengadilan Klaten lagi. Sial bener deh aku :p).
Sembari si polisi menulis surat pengganti STNK-ku yang ditahan aku jadi terbayang kejayaan masa silam, tepatnya 6 tahun lalu. Sewaktu kelas 3 SMP sering dolan sama Novita ke Delanggu ke rumah teman-teman kami tersayang, terutama buat latihan nari dan sekedar nongkrong, gojek, dan mencari bahan ketawaan yang bikin geli kalau diingat. Pernah waktu itu aku, Novita, dan Indru bertiga boncengan “telon” tanpa helm melewati jalan kecil persawahan sepi hendak ke rumah Saridol Ipah di seberang desa. Eeeee lha kok sial banget di area lingkungan desa dan sawah-sawah ketemu sepasang bapak-bapak Polisi yang siap menerkam mangsa! Kami langsung dicegat dan dibawa ke pos polisi Pakis, dan Indru pun dapat jatah mbonceng pak polisi, sementara aku mbonceng Novita. Hahahaa… teringat Indru pasrah diboncengin polisi aja udah bikin aku ngakak banget. Apalagi teringat sewaktu di pos polisi, si novita langsung nelfon ayahnya yang notabene seorang polisi kantoran (bukan polisi jalanan) kalau dirinya ditilang. Langsung deh kedua polisi yang menangkap kami langsung saling melirik, dan berkata lirih “ternyata yang kita tangkep anak polisi…” trus habis itu kami nggak jadi ditilang, cuma dinasehati dan disuruh pergi gitu aja. Bikin aku ngakak berat deh…
Jadi tiap kali ditilang aku terbayang kejadian itu, dimana pada masa lalu tiap kena tilang bareng Novita selalu bisa meloloskan diri dengan selamat tanpa keluar uang sepeser pun gara-gara bapaknya Novita adalah seorang polisi juga. Lolos dari pos polisi dengan muka lega berseri-seri, nggak kaya orang yang hebis keluar dari penjara karena mencuri sesuatu. Hahahaa…
Di pos polisi depan Plasa Matahari Klaten pun aku senyum-senyum geli mengingat kejadian itu. Sampe-sampe suara si polisi yang kelar menulis-nulis pun mengagetkanku “Apa ada yang lucu?!” dengan muka sinis dikira aku menertawakannya, “eh, enggak kok…” jawabku. Ah pak polisi ini, udah menyebalkan, menjengkelkan pula. Sial banget deh si polisi nih..
Jadinya nih ya, tanggal 9 Maret besok aku harus ambil STNK motorku tersayang di pengadilan Klaten. Jauhnyaaa dari Jogja, kan sorenya aku harus kuliah Sistem Penghantaran Obat (ngulang). Hmmm sabar.